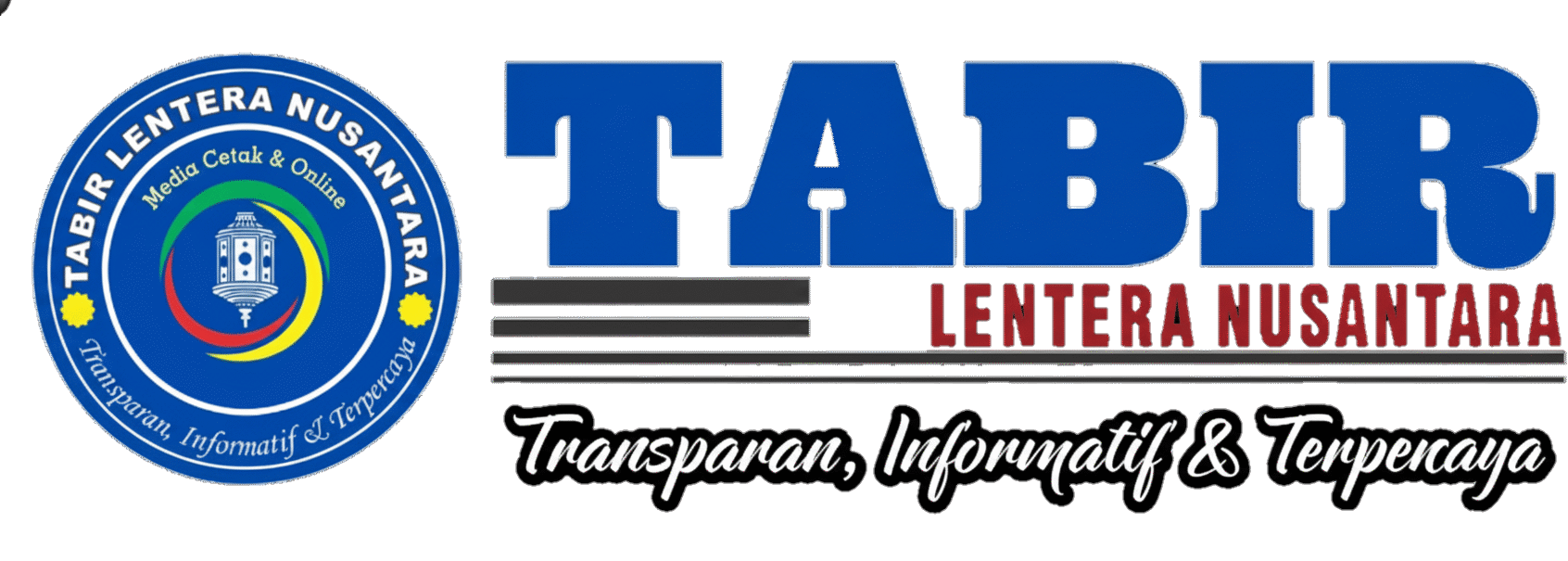Ditulis pada: Jumat, 20 Desember 2025
Surabaya —Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui UU Nomor 1 Tahun 2024 dimaksudkan untuk meredam pasal multitafsir dan memperkuat kepastian hukum. Namun dalam praktik, budaya viral, percakapan WhatsApp, dan militansi fandom justru menghadirkan risiko hukum baru bagi masyarakat.
Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada awal 2024. Revisi ini dilakukan sebagai respons atas kritik publik yang berkembang selama bertahun-tahun terkait penggunaan pasal-pasal UU ITE yang dinilai multitafsir dan kerap menjerat warga akibat aktivitas digital sehari-hari.
Selama penerapannya, UU ITE kerap dikaitkan dengan perkara pencemaran nama baik, ujaran di media sosial, hingga percakapan di aplikasi pesan instan. Situasi tersebut mendorong lahirnya pembaruan regulasi dengan tujuan meningkatkan kepastian hukum dan mencegah kriminalisasi berlebihan terhadap ekspresi warga di ruang digital.
Salah satu perubahan utama dalam revisi ini adalah pengaturan ulang ketentuan pencemaran nama baik melalui Pasal 27A. Pasal tersebut secara eksplisit mengatur unsur “menuduhkan sesuatu” dan syarat “diketahui umum” sebagai elemen yang harus dipenuhi. Selain itu, regulasi ini juga menegaskan kembali kedudukan informasi elektronik dan hasil cetaknya sebagai alat bukti yang sah dalam proses hukum.
Meski demikian, praktik di lapangan menunjukkan bahwa tantangan belum sepenuhnya teratasi. Aplikasi pesan instan seperti WhatsApp, yang oleh sebagian besar masyarakat dipersepsikan sebagai ruang komunikasi privat, masih kerap menjadi pintu masuk perkara hukum. Percakapan informal, pesan emosional, atau tangkapan layar yang tersebar di luar konteks awal tidak jarang memicu laporan hukum.
Berdasarkan ketentuan UU ITE, informasi elektronik dan hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti yang sah. Pengadilan juga menerima percakapan digital sebagai bagian dari pembuktian, sepanjang keasliannya dapat diverifikasi sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.
Menurut Seno Aji, S.Sos., S.H., M.H, analis kebijakan dan praktisi hukum, perubahan norma dalam UU ITE belum serta-merta mengubah pola penegakan hukum maupun perilaku masyarakat dalam bermedia digital. Ia menilai terdapat jarak antara tujuan regulasi dan realitas praktik sosial.
“UU ITE versi terbaru memang lebih rapi secara teks. Namun persoalan utama kita bukan hanya di norma, melainkan di praktik sosial dan penegakan hukum. Ketika budaya viral, lapor-melapor, dan tangkap layar masih menjadi kebiasaan, maka risiko kriminalisasi tetap tinggi,” ujar Seno Aji dalam keterangannya.
Ia menjelaskan, banyak perkara hukum yang bermula dari percakapan spontan tanpa niat jahat. Dalam situasi tertentu, satu kalimat di grup WhatsApp dapat ditafsirkan sebagai tuduhan ketika dibaca terpisah dari konteks awal, lalu dikonstruksi sebagai bukti permulaan dalam proses hukum.
Kondisi tersebut, menurut Seno Aji, menimbulkan ilusi keamanan semu di tengah masyarakat. Banyak orang beranggapan bahwa percakapan chat bersifat sepenuhnya privat dan tidak memiliki konsekuensi hukum.
“Banyak yang merasa aman karena berpikir ‘ini hanya chat’. Padahal secara hukum, percakapan digital dapat menjadi bukti permulaan yang serius. Screenshot yang tersebar tanpa konteks dapat membangun narasi hukum yang merugikan seseorang,” kata Seno Aji.
Persoalan menjadi semakin kompleks ketika dinamika ini bertemu dengan budaya fandom. Loyalitas yang kuat terhadap figur publik, baik di bidang hiburan maupun politik, melahirkan praktik kolektif seperti cancel culture, mass report, hingga penyebaran tuduhan di ruang digital.
Dalam kajian sosial, fandom kerap bergerak dengan logika kerumunan, di mana tindakan menyerang pihak lain dianggap wajar selama dilakukan atas nama solidaritas kelompok. Namun dalam konteks hukum, setiap pernyataan digital tetap melekat pada tanggung jawab individu.
“Di titik ini, banyak orang lupa bahwa tanggung jawab pidana itu personal, bukan kolektif. Ikut-ikutan menyerang atau memviralkan tuduhan tetap berpotensi berujung proses hukum,” jelas Seno Aji.
Selain isu pencemaran nama baik, aktivitas fandom juga bersinggungan dengan persoalan hak cipta. Fanworks yang dikomersialkan tanpa izin pemilik hak dapat menimbulkan konsekuensi hukum, meskipun dilakukan atas dasar ekspresi kecintaan terhadap figur tertentu.
Di tingkat sosial yang lebih luas, kombinasi antara UU ITE, budaya viral, dan militansi digital memunculkan kecenderungan masyarakat untuk membatasi ekspresi di ruang digital. Banyak warga memilih bersikap pasif bukan karena memahami batas hukum, melainkan karena takut berhadapan dengan proses hukum.
Fenomena tersebut berdampak pada kualitas diskursus publik. Media sosial yang semula menjadi ruang dialog perlahan berubah menjadi arena pengawasan sosial, di mana setiap pernyataan berpotensi dipantau, direkam, dan dilaporkan.
Seno Aji menilai kondisi ini sebagai tantangan serius bagi demokrasi digital. Menurutnya, tujuan utama UU ITE seharusnya melindungi warga negara, bukan menciptakan iklim ketakutan dalam berekspresi.

“Jika ruang digital hanya diisi oleh ketakutan dan serangan massal, yang hilang bukan hanya kebebasan berekspresi, tetapi juga kualitas percakapan publik,” ujarnya.
Kajian ini menunjukkan bahwa solusi tidak dapat berhenti pada revisi regulasi semata. Literasi hukum digital menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat umum, termasuk pemahaman mengenai batasan ekspresi, risiko penyebaran konten, serta konsekuensi hukum dari aktivitas digital.
Di sisi lain, aparat penegak hukum juga dituntut untuk menerapkan UU ITE secara hati-hati, proporsional, dan tidak reaktif terhadap tekanan viral. Prinsip praduga tak bersalah dan verifikasi yang cermat tetap menjadi fondasi utama dalam penegakan hukum.
Pada akhirnya, pertanyaan mendasar bukan hanya apakah UU ITE telah diperbaiki secara normatif, melainkan apakah masyarakat dan institusi siap menggunakannya secara adil dan bertanggung jawab. Tanpa perubahan budaya bermedia dan peningkatan pemahaman hukum, ruang privat akan terus berpotensi bergeser menjadi ruang pidana, dengan WhatsApp tetap menjadi salah satu sumber risiko hukum yang sering luput disadari publik.