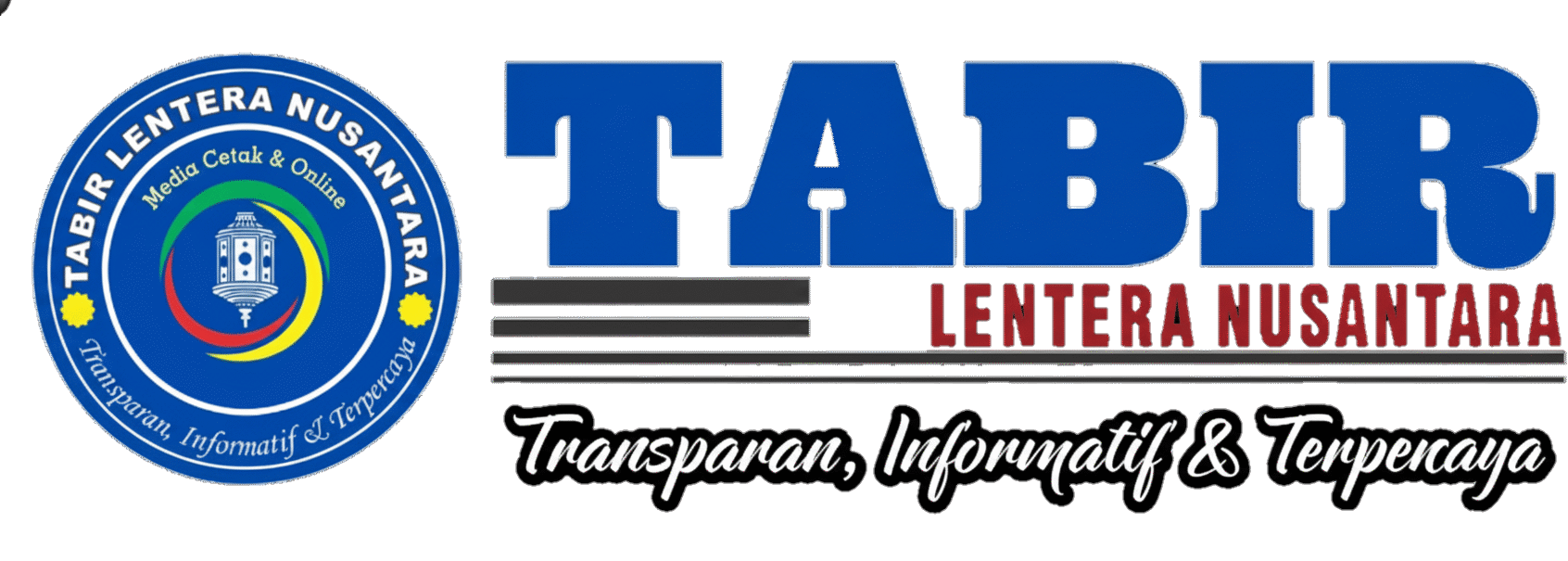Surabaya — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, kembali menekankan urgensi pergeseran paradigma dalam pemberian pekerjaan rumah (PR) bagi siswa di Indonesia. Dalam upayanya mentransformasi budaya literasi nasional, Mu’ti mengimbau agar para guru tidak lagi membebani siswa semata-mata dengan pengerjaan soal-soal latihan akademis, melainkan memberikan tugas yang menstimulasi kognitif dan imajinasi, seperti meresensi buku. Pernyataan strategis ini disampaikan Mu’ti saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) XX Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) pada pekan lalu, Rabu (19/11/2025), dan terus menuai respons dari berbagai kalangan akademisi hingga hari ini.
Menurut Abdul Mu’ti, esensi pendidikan dasar dan menengah seharusnya tidak terkungkung pada kemampuan teknis menjawab soal ujian, tetapi lebih pada pembangunan nalar yang jernih dan kritis. “Pekerjaan rumah (PR) itu penting, tetapi bukan hanya mengerjakan soal. PR mestinya menugaskan anak membaca dan menulis, seperti membuat resensi atau review buku,” tegas Mu’ti. Ia menambahkan bahwa ruang aktualisasi dan imajinasi anak harus dibuka seluas-luasnya untuk mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, namun juga literat dan mampu berpikir mendalam.
Merespons wacana tersebut, pakar pendidikan dari Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Sri Lestari, memberikan apresiasi sekaligus catatan kritis pada Rabu (26/11/2025). Sri menilai inisiatif Mendikdasmen sebagai langkah progresif untuk melatih kemampuan analisis (analytical skills), evaluasi, dan argumentasi siswa yang merupakan komponen vital dalam literasi tingkat lanjut. Namun, ia mengingatkan pemerintah untuk tidak menutup mata terhadap realitas empiris di lapangan, di mana kemampuan siswa dalam memahami teks panjang secara komprehensif masih menjadi kendala utama.
“Karena itu, kewajiban membuat resensi perlu diiringi dengan pendampingan literasi dasar, pemantauan kemampuan membaca siswa, dan pembelajaran bertahap tentang cara menyusun resensi yang baik,” ujar Sri dalam keterangan resminya di Surabaya. Tanpa pendampingan pedagogis yang tepat, kebijakan ini dikhawatirkan hanya akan menjadi beban administratif baru bagi siswa tanpa dampak substansial pada kemampuan literasi mereka.
Lebih jauh, Sri menyoroti tantangan infrastruktur pendidikan yang masih timpang, khususnya terkait ketersediaan bahan bacaan. Menurutnya, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada pemerataan akses terhadap buku yang berkualitas. “Jika pemerintah ingin mewajibkan resensi, maka tanggung jawab menyediakan buku berkualitas juga harus berjalan seiring, baik melalui pengadaan buku fisik, pembaruan koleksi perpustakaan, maupun penyediaan akses buku digital secara merata, terutama di daerah pinggiran,” imbuhnya.
Isu kompetensi dan beban kerja guru juga menjadi sorotan tajam dalam analisis Sri. Ia menekankan bahwa sebelum menuntut siswa menjadi literat, guru sebagai garda terdepan pendidikan harus memiliki kompetensi literasi yang mumpuni. Sri menyarankan adanya workshop penulisan resensi dan insentif publikasi untuk memacu semangat guru berkarya. Namun, ia mengakui fakta di lapangan sering kali kontraproduktif; guru kerap terjebak dalam padatnya jam mengajar dan tumpukan beban administrasi yang menyita waktu pengembangan diri.
Sebagai alternatif solusi untuk membangun ekosistem literasi yang berkelanjutan, Sri mengusulkan revitalisasi media sekolah seperti majalah dinding (mading) atau majalah sekolah, serta penyelenggaraan pameran karya literasi siswa secara berkala. “Keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan ekosistem pendukung: perpustakaan yang memadai, guru yang literat, kurikulum yang terintegrasi, dan kemampuan dasar siswa yang diperkuat. Tanpa itu semua, kebijakan ini berisiko tidak mencapai tujuannya,” tutup dosen Fakultas Pendidikan UM Surabaya tersebut.